Arini bergeming mendengar kabar kedatangan ibunya.
"Hei ... kok diam? Besok ibumu mau nengok kita di sini. Ceria dikit, napa!"
Arini memandangku sekilas sambil mengangkat bahunya. Bibirnya ditarik ke atas seolah mau bilang, "Mau gimana lagi?"
Selalu begitu responsnya jika Bu Marisa, mama Arini, akan datang. Aku tidak bisa menebak bagaimana perasaan Arini. Senangkah? Tak mungkin raut seperti itu masuk kategori senang. Bencikah? Masa sama ibu kandung sendiri benci?
Arini, aku mengenalnya dua tahun terakhir ini, sejak aku ngekos bareng di daerah sekitaran kampus. Arini yang kukenal biasanya selalu ceria. Arini yang baik dan rajin. Arini yang selalu sopan dan santun kepada siapa pun, apalagi kepada orang yang lebih tua. Kecuali untuk yang satu ini, aku sungguh tidak mengerti. Arini hampir selalu dingin setiap menghadapi ibunya.
Beberapa kali dalam setahun, Bu Marisa menyempatkan diri berkunjung ke tempat kos kami. Aku sendiri sudah merasa akrab dengannya. Pada mulanya aku tak begitu menyadari aura dingin di antara keduanya. Saat duduk di hadapan ibunya, Arini hanya bersimpuh. Hanya sedikit kata yang meluncur dari bibirnya. Sekadar basa-basi, "Mama mau minum apa? Sudah makan atau belum?" Selebihnya, dia membisu. Untuk mengurangi kecanggungan, Bu Marisa terkadang bertanya tentang perkuliahan atau keadaan kos. Aku, yang berada di antara mereka, berperan sebagai pemecah keheningan.
"Rin, kamu ada masalah ya, sama ibu kamu?" tanyaku suatu hari.
Arini mengelak. "Ah, biasa aja."
"Biasa gimana? Anak-ibu kan biasanya akrab," bantahku.
"Aku emang begini di rumah. Enggak suka bermanja-manja."
"Maksudku ...."
"Maaf ya, Bi. Jangan bahas itu, ya!" pintanya sendu.
Arini terlihat tak suka jika aku membahas tentang keluarganya. Yang aku tahu, berdasarkan informasi yang kudapat selintas dari obrolan bersama ibunya, Arini mempunyai seorang adik laki-laki yang duduk di bangku sekolah menengah.
Aku tidak berniat turut campur dengan masalah keluarga Arini, tetapi hatiku tidak bisa dibohongi, pasti ada sesuatu di antara dia dan ibunya. Sebagai mahasiswi jurusan psikologi, sedikit banyak aku tahu gejala ketidaksehatan mental orang-orang di sekitarku.
Ah, Arini. Aku jadi sering memikirkan sikapnya.
Kunjungan Bu Marisa semakin intens. Hampir tiap bulan Bu Marisa menyempatkan diri melihat Arini, memastikan anak gadisnya tak kekurangan apa pun. Bu Marisa seorang pengusaha makanan, jadi wajar jika hanya untuk mengenyangkan satu perut, bukanlah kewajiban yang membebani. Bahkan aku pun ikut merasakan kasih sayangnya. Menurutku, Bu Marisa memang penyayang. Lembut dan enggak pelit, bahkan pada diriku yang orang asing ini. Jarak tiga jam perjalanan dari rumahnya ke kosan kami bukanlah penghalang bagi Bu Marisa menunjukkan perhatiannya. Lalu, Arini?
Jangan tanya seperti apa. Seumur hidupku belum pernah kusaksikan dinginnya sikap seseorang melebihi dinginnya Arini pada ibunya. Sopan, tapi dingin. Baik, tapi tak hangat. Sulit kujabarkan dengan kata-kata. Semua serba formalitas. Kupikir Bu Marisa pun merasakannya. Bagaimanapun batin seorang ibu jelas lebih peka. Namun, aku melihat seolah-olah Bu Marisa berusaha tak mengindahkan fakta itu. Seperti dua orang yang sedang bersikukuh mengadu ketahanan masing-masing. Hubungan yang rumit, menurutku.
Hingga suatu hari, mulutku menganga. Aku terlambat pulang ke kosan karena harus mengerjakan beberapa tugas kelompok hingga sore. Saat langkah kakiku memasuki halaman kosan yang sempit, sebuah mobil berwarna perak terparkir di pinggir jalan. Aku sudah bisa menebak siapa yang datang. Dengan riang aku bersenandung, lalu kuucapkan salam. Tanpa ragu kudorong pintu yang setengah terbuka. Ruangan kos yang tak terlalu luas itu menyuguhkan pemandangan yang tak bisa kuterima dengan akal sehatku.
Bu Marisa bersimpuh dalam derai air mata. Tangannya mendekap betis Arini. Arini sendiri berdiri tegak mematung memalingkan tubuhnya dari sang ibu. Wajahnya kelam dan membesi. Matanya nanar menatap tembok. Kusangka anak dan ibu sama tersedu, nyatanya pipi Arini kering. Aku tak bisa menafsirkan apa isi hatinya. Datar. Sedatar tembok di hadapannya.
Menyadari kedatanganku Arini menoleh. Sekilas kutangkap perasaan tak nyaman di wajahnya. Sebuah kalimat terlontar dari bibir indahnya. "Mama, enggak usah datang lagi ke sini. Rini enggak akan berubah." Suaranya pelan.
Tanpa menunggu respons siapa pun, Arini secepat kilat menyambar tas selempang andalannya, yang teronggok tak jauh dari jangkauan tangannya. Tergesa Arini menuju pintu. Pundaknya membentur pundakku. Aku meringis. Arini sempat berhenti dan menatapku sekilas. Dari gerakan bibirnya kueja kata maaf. Kemudian, sosoknya melesat menghilang dari pandangan.
Bu Marisa melolong, menyebut nama anak gadisnya. Tangisannya demikian pilu. Aku memburu dan memeluknya. Ada apa denganmu, Arini? Kenapa kau biarkan seorang ibu menderita seperti ini?
Beberapa saat kubiarkan Bu Marisa mengurai isakannya. Setelah terlihat sedikit tenang, kuasongkan segelas air hangat. Aku tak sanggup bertanya meskipun hatiku berteriak ingin tahu. Dalam usia persahabatan kami ini, bagaimanapun Arini sudah menjadi bagian hidupku. Ibunya sudah kuanggap ibuku. Sakit di jiwanya membuat hatiku resah.
"Ini salah mama," ucap Bu Marisa.
"Ini salah mama," ulangnya sambil menunduk. Dari suaranya, aku tahu dadanya sesak. Aku menunggu.
"Arini anak yang baik. Tidak pernah nakal. Tidak pernah menuntut apa pun. Mama ... terlalu keras padanya. Mama ... sering memukulnya. Mama ... mama ... menyiksanya lahir batin." Pita suaranya seperti tercekik. Bu Marisa kembali terisak. Di antara isak yang tersisa, cerita itu mengalir. Tenggorokanku hampir tersekat.
"Dari kecil dia anak yang manis. Apalagi waktu adiknya lahir, dia seolah mengerti bahwa mamanya sedang repot. Karena itu, dia lebih dekat dengan ayahnya, tapi ... untung tak dapat diraih malang tak dapat ditolak. Ayahnya tiba-tiba pergi untuk selamanya." Air mengambang di sudut netra Bu Marisa.
"Kecelakaan itu begitu tiba-tiba. Mama limbung kehilangan pegangan. Tak ada sanak saudara tempat bergantung. Terseok-seok mempertahankan hidup dengan dua balita yang sedang membutuhkan perhatian. Mama sering abai. Bukan cuma itu, sedikit kenakalan Arini ... ah, bukan kenakalan besar, hanya rengekan anak usia lima tahun, tapi buat mama saat itu, rengekan itu demikian mengganggu. Tanpa sadar mama kerap membentak, mencubit, mengurung, dan memukul hingga lebam." Sekali lagi Bu Marisa mengguguk.
"Mama tidak tahu kalau luka itu akan terbawa sampai dewasa. Arini tak pernah mengeluh, tetapi sebagai gantinya Arini tak pernah mau mama sentuh, sedikit pun!"
Hatiku basah. Turut merasakan kepedihan seorang ibu, juga Arini. Duhai, anak sekecil itu menerima perlakuan tak manusiawi dari orang yang paling dikasihinya. Jika ibunya saja seolah tak menghendaki kehadirannya, lalu siapa lagi yang akan menerimanya?
Di balik wajahnya yang ramah, Arini menyimpan ketidakpercayaan pada siapa pun. Karena masa kecilnya tersakiti, sampai dewasa dia kehilangan rasa aman. Bagi Arini, kedekatan dengan seseorang adalah ancaman. She does feel insecure! Pantas saja dia tak pernah membuka diri, termasuk padaku.
"Tolong jaga Arini, ya, Nak. Hanya Nak Kayla yang mama percayai," ujar Bu Marisa sebelum pamit.
Sejak peristiwa sore itu, Bu Marisa tak pernah menginjakkan kaki di kosan. Bu Marisa sering menghubungiku lewat telepon untuk menanyakan segala hal tentang Arini, termasuk kebutuhannya. Arini tetap pulang ke rumah orang tuanya saat liburan. Aku tak berani mencari tahu seperti apa interaksi ibu dan anak itu saat di rumah.
Suatu hari di akhir liburan, Bu Marisa memberi kabar Arini sakit, mengharuskannya beristirahat di rumah selama tiga bulan. Aku segera mengurus cuti kuliah Arini seperti permintaan Bu Marisa. Aku meluncur menyambangi sahabat istimewaku itu.
Tak banyak informasi yang kudapat tentang penyakit Arini, kecuali bahwa sakitnya berhubungan dengan jantungnya. Tak elok jika kutelisik lebih jauh.
Pilu hati ini melihat tubuh Arini demikian ringkih. Mukanya pucat tak berona. Seluruh waktunya dia habiskan di rumah dengan aktivitas yang tidak boleh memberatkan. Seulas senyum menghias raut wajahnya menyambut kedatanganku. Kupeluk erat tubuhnya. Aku merindukannya. Sepanjang hari kuhabiskan menemaninya di rumah. Bercerita tentang hal-hal ringan di kampus.
Ada yang berubah dari hubungan Arini dan Bu Marisa. Itu yang tertangkap mataku. Saat Bu Marisa membawakan makanan untukku dan untuk Arini, dia tersenyum pada ibunya. Lalu, saat Bu Marisa menyuapkan segarpu buah, Arini membuka mulutnya dengan antusias. Ya, Allah. Ada apa ini? Aku bahagia, sungguh bahagia. Namun, apa yang membuatnya berubah?
Aku yang bahagia tak henti-hentinya menyunggingkan senyum. Rupanya Bu Marisa menangkap tanya di hatiku.
"Arini masih lemah. Jadi, sementara waktu enggak bisa banyak bergerak. Maaf, ya, Nak Kayla. Arini mama yang suapin. Jangan dilihat gede umurnya," kelakar Bu Marisa.
"Mama ...." Arini tersipu. Wajahnya sedikit merona. Tangannya mencubit mesra ibunya.
Tiba-tiba wajah ibu setengah baya itu meringis dibuat-buat. "Duh, Arini! Mama sakit, nih. Mau balas mama, ya? Gara-gara mama sering nyubit waktu kamu kecil, sekarang pas mama udah tua, gantian kamu yang nyubit?"
Aku tersentak mendengar canda Bu Marisa. Kulirik Arini. Mimiknya berubah cemberut.
"Masa segitu aja sakit? Sini, Rini tiupin, biar sakitnya kebawa angin." Ditariknya tangan sang ibu dan didekatkan ke mulutnya. Lalu, ….
Grkkk!
Digigitnya tangan Bu Marisa dan dilepaskannya. Tawanya berderai, memamerkan gigi putihnya yang berderet sempurna. Tawa mereka memenuhi kamar bernuansa krem itu. Aku melongo. Kekanak-kanakan, tapi manis.
Sore hari kuputuskan untuk pulang. Sebelum aku melangkah keluar, Bu Marisa memelukku erat. "Terima kasih, Nak Kayla. Sepertinya nasihat Nak Kayla masuk ke hati Arini."
"Nasihat yang mana?" Aku menatap Bu Marisa.
"Arini sedikit demi sedikit membuka hati. Apalagi sejak dia sakit dua bulan lalu, Mama enggak berhenti menyentuh dan mendekatinya. Awalnya ia menolak, lama-lama membiarkan. Awalnya canggung, lama-lama terbiasa. Semua itu kata Arini karena nasihat Nak Kayla. Arini sedang belajar memaafkan. Mama enggak akan memaksa Arini buru-buru memaafkan mama. Mama akan menunggu Arini sembuh. Ternyata sakit Arini besar sekali hikmahnya buat kami."
Hatiku lega. Aku tahu Arini butuh waktu untuk mengobati luka hatinya yang paling dalam. Sebelum memaafkan ibunya, dia harus berdamai dengan dirinya sendiri. Menerima dirinya sebagai pribadi yang berharga sehingga ia akan mulai merasa aman menerima perhatian dan kasih sayang orang lain, tanpa takut ditolak atau dikhianati. Allah Maha Pengasih dan Penyayang.
***
Tentang Penulis:
Penulis dilahirkan di Bandung, 37 tahun lalu. Selain berstatus sebagai ibu rumah tangga, penulis juga berprofesi sebagai guru SD di daerah domisilinya, bagian selatan kota Bandung. Menulis adalah suatu kebutuhan, demikian kata penulis. Bersama sahabatnya pernah menulis buku Inilah Pesan Penting di Balik Berkah dan Manfaat Silaturahmi (Ruang Kata, 2012), tahun 2020 menulis lebih dari 10 antologi, dan awal tahun 2021 ini baru launching karya solo berupa novel perdananya berjudul "Ketika Harus Memilih." Penulis bisa dihubungi via IG: @rg_numilah.
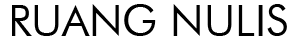


Aku paham menjadi arini,
ReplyDeleteSosok arini adalah aku d masa lampau,
Paham jika berdamai yg utama adalah dengan diri sendiri,
Dulu aku pun begitu,luka d masa lampau benar2 begitu sulit untuk d selesaikan.
Mohon izin untuk menjadikan cerpen ini sebagai bahan ajar pelajaran Bahasa Indonesia di kelas. Cerpennya menarik dan mengandung pesan moral yang tinggi.
ReplyDelete