Oleh: Dwi Endah Ni'matul Amalia
@endahamalia224
Mataku menatap jarum jam yang terus berputar. Tepat pukul dua belas malam. Aku tidak bisa terpejam, kenyataan itu masih jelas dalam ingatan. Bukan seperti bunga tidur yang menjadi semu ketika bangun, ini terasa menyesakkan. Di luar angin berhembus begitu kencang, menyelinap masuk di kamar sempit yang hanya berukuran 3 x 3 meter. Aku semakin membeku bersama kekecewaan.
***
Azan subuh berkumandang saat aku membuka mata. Ternyata aku terlelap setelah menghabiskan setengah malam dengan tangisan. Setengah badanku kuyup, mungkin karena air mata mengalir terlalu deras. Bukan. Hujan sedang turun lebat, genteng kuno tempias persis di atas ranjang. Aku ber-puh pelan.
"Nem…Nem…Cepat bangun!" Suara Mamak meneriakiku.
Aku segera beranjak dari kamar dan mendapati tempias di hampir semua titik. Mamak sedang keteteran memindahkan ember dari satu titik yang bocor ke titik lainnya, sementara adikku menangis di pojokan yang tidak bocor, masih mengantuk. Aku turun tangan membantu.
"Kau ini anak gadis, seharusnya kau bangun lebih awal membantu Mamak di dapur. Belum matang merebus ubi, hujan ini turun membuat api di tungku mati."
Sudah biasa Mamak marah kepadaku saat ada hal yang membuatnya jengkel. Aku memilih diam karena percuma berbicara, Mamak akan tetap menyalahkanku meskipun aku benar. Sejak Bapak meninggal dua tahun silam, hanya Mamak tulang punggung keluarga untuk menghidupi aku dan adikku yang tidak tumbuh seperti anak-anak sebayanya. Ia dinyatakan menderita autisme sejak umur 10 bulan, sekarang ia berusia 7 tahun. Dalam kondisi yang kekurangan ini, tidak ada biaya untuk mengobati Naja. Itulah yang membuat Mamak seringkali mudah marah.
Waktu sudah menunjukkan pukul 08.00 tetapi mentari belum menampakkan dirinya. Walaupun hujan sudah reda, awan-awan masih menutupi langit.
"Bergegas kau pergi, Nem. Ini sudah terlambat dari biasanya gara-gara hujan tidak segera reda," omel Mamak sambil menyerahkan keranjang dagangan berisi kue lapis ubi.
"Baik, Mak. Nem pamit. Assalamu'alaikum."
"Wa'alaikumussalam. Semoga daganganmu habis, Nem," ucap Mamak seraya berpaling masuk ke dalam rumah.
Aku tersenyum mengamini doa Mamak. Kemudian, menuntun sepeda ontel tua milik Bapak yang kunaiki setelah melewati gang sempit menuju rumah. Semua jalanan dipenuhi air sisa hujan tadi, sedikit menyusahkan perjalananku karena alas kaki dan roda sepeda dipenuhi tanah yang basah. Sudah dua tahun sejak hari pertama masuk kelas 8, setelah Bapak meninggal, aku menjajakan kue buatan ibu di sekolah. Tidak selalu habis, maka aku berkeliling di area perkampung dan pantang pulang sebelum isi keranjang telah kosong.
Pagi ini cukup sepi, sepertinya orang-orang masih enggan keluar rumah sebab udara dingin begitu menusuk tubuh. Aku sampai di depan gerbang SMP-ku dulu. Ya, aku telah lulus dari seragam biru putih. Di dalam sekolah tampak sedang mengadakan upacara bendera, sementara di luar para orang tua melongak-longok di tepi pagar. Aku baru ingat, ini hari pertama tahun ajaran baru. Seketika perkataan Mamak kala itu terngiang dalam pikiranku.
"Kau ini jangan banyak berharap bisa melanjutkan sekolah, Nem. Mamak hanya penjual kue yang penghasilannya tak seberapa, untuk sehari-hari saja kurang apalagi untuk membayar sekolah yang sampai jutaan itu," ujar Mamak ketika aku baru pulang sekolah, di hari terakhir ujian.
Demi mendengar itu, semua harapan yang sudah kutata rapi langsung pupus begitu saja. Aku tidak bisa melawan, hanya diam dan menangis. Setiap malam bahkan aku selalu menangisi kenyataan pahit ini.
Aku memilih pergi dari keramaian sekolah daripada harus menahan sesak di dada.
Seandainya Bapak masih ada, mungkin keadannya tidak akan seperti ini. Batinku.
***
Sudah sepekan aku menghindari berjualan di sekolah. Meskipun harus mengayuh sepeda lebih jauh, aku rela melakukannya. Jujur, aku masih belum ikhlas menerima keadaanku yang seperti ini. Setelah berkeliling jauh, aku beristirahat di bawah pohon besar. Aku menangkupkan kedua tangan di depan wajah dan duduk di sebuah bangku yang panjangnya hanya satu meter.
"Ambillah," ucap seseorang dengan suara agak berat.
Aku membuka kedua tangan dari wajah, sebuah tangan menyodorkan sebotol air mineral kepadaku. Aku mendongak.
"Ambillah," ucap orang tersebut sekali lagi.
Ia sudah duduk menjajariku saat aku masih bergeming menatap sosok di hadapanku. Aku sama sekali tidak mengenal orang ini.
"Kamu sepertinya kelelahan, minumlah," ujarnya penuh perhatian.
"Terima kasih." Kata pertama yang keluar dari mulutku setelah terdiam cukup lama, sambil meraih botol air mineral darinya.
Panas matahari masih terasa menyengat, padahal sudah pukul 4 sore. Takada percakapan membuat suasana kaku. Aku sedikit mencuri pandang, ia sedang melihat ke arah jalan raya yang ramai oleh kendaraan.
"Namaku Bona, tapi aku suka dipanggil Abang Bona. Hampir setiap hari aku mengunjungi tempat ini, menghabiskan sisa sinar mentari di bangku ini."
"Maaf, aku telah singgah di bangkumu."
"Tidak masalah, ini tempat umum jadi aku tidak punya hak untuk melarang siapa pun yang duduk di sini."
Aku kembali terdiam.
"Siapa namamu?"
"Nem."
"Nem?"
"Iya. Sebenarnya namaku Nimas, tapi orang-orang memanggilku Nem."
Pertemuan pertama antara aku dan Abang Bona ternyata berlanjut pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kami semakin akrab dan saling mengenal lebih jauh. Sesekali ia menemaniku berjualan. Ia merupakan pemuda yang cerdas, saat ini sedang berkuliah memasuki tahun ke tiga di salah satu kampus terbaik. Ia sudah tahu kalau aku hanya lulusan SMP, maka setiap bertemu ia selalu menyempatkan waktu untuk mengajariku materi pelajaran. Istilahnya guru privat. Terkadang aku merasa minder di depannya, tetapi ia tidak pernah bosan menasihatiku layaknya adik dan kakak. Aku sayang Abang Bona.
***
Suatu malam saat aku baru merebahkan tubuh di atas kasur, terdengar bunyi sesuatu yang pecah. Aku kembali bangkit dan keluar dari kamar. Aku menemui Naja yang sedang menangis, dan bunyi tadi berasal dari gelas kaca yang sengaja dipecahkan olehnya. Naja memang sering mengamuk tanpa alasan, ia tidak bisa ditinggal sendiri. Kupikir tadi ia sudah tertidur nyenyak, maka aku meninggalkannya di kamar karena seluruh tubuhku terasa pegal. Mamak sedang ke warung membeli beras. Saat Mamak tidak ada, giliran aku yang menjaganya. Aku harus membuatnya selalu tenang. Baiklah. Aku menggendong Naja kembali ke kamar untuk menidurkannya.
"Kenapa ada pecahan gelas di sini?" Terdengar suara Mamak yang baru pulang.
Setelah memastikan Naja sudah terlelap, aku bangun pelan-pelan dan menemui Mamak.
"Maaf, Mak, tadi Naja yang melakukannya," ucapku sambil tertunduk.
"Kau tidak bisa menjaganya dengan baik, Hah? Baru saja Mamak tinggal sebentar." Nada suara Mamak meninggi.
Aku tidak menjawab apa-apa. Aku memilih membereskan pecahan gelas tadi dan bergegas masuk ke kamar.
Tuhan, Nem rindu Bapak. Dalam keadaan seperti ini, hanya Bapak yang selalu bisa menenangkan hatiku. Nem sungguh ingin bertemu Bapak. Aku menangis dengan awan hitam menyelimuti kalbu.
***
Dua tahun telah berlalu lagi. Hari ini, Abang Bona resmi diwisuda. Ia telah memberitahu sejak jauh-jauh hari, maka aku sengaja menyisihkan sedikit uang hasil jualan untuk membelikannya sesuatu. Kemarin malam aku begitu riang membungkus kado ini, tidak sabar menanti besok. Bahkan, aku sengaja datang lebih awal sebelum pukul 4 sore. Saat melihat Abang Bona mendekat dengan masih memakai baju wisudanya, aku tersenyum bahagia. Ia berlari-lari lalu tanpa menyapa, ia langsung memelukku erat sekali. Ada apa? Aku bingung, tetapi tidak mau berperasangka buruk. Aku balas memeluknya.
Di bawah pohon yang besar ini, aku dan Abang Bona duduk di bangku yang sama seperti awal bertemu. Kali ini tidak banyak percakapan seperti biasanya, apalagi canda dan tawa. Aku lebih banyak diam, sementara Abang Bona hanya tertunduk ingin mengatakan suatu hal tetapi mulutnya tidak mampu membuka.
"Aku sungguh senang bersahabat denganmu, Nem. Menghabiskan sisa siang di sini bersamamu. Aku tidak pernah berpikir untuk meninggalkanmu, semua ini terjadi bukan atas kemauanku."
Ia tak lagi menahan tangis, begitu pula aku. Mata basah kami saling bertemu, ia menggenggam erat tanganku. Mengapa? Hatiku bertanya tidak mengerti.
"Maafkan, Abang. Abang…harus pergi," ucapnya terbata-bata seraya melepas tanganku.
Aku tidak bisa mencegahnya, meski banyak pertanyaan yang ingin kusampaikan. Tubuhku terlalu lemah untuk bangkit. Abang Bona telah pergi. Cukup lama aku hanya bergeming, menatap punggungnya yang sudah hilang dari pandangan. Mataku baru menyadari ada sebuah plastik hitam di sampingku. Tanganku meraih plastik tersebut dan membukanya. Hanya berisi buku-buku. Ini milik Abang Bona, aku ingat jelas ia sering mengajariku dengan buku-buku ini.
Aku masih belum mengerti. Setelah hari-hari kami lewati bersama, mengapa ia begitu tega meninggalkanku tanpa kejelasan? Mengapa? Aku pikir Abang Bona adalah sosok pengganti Bapak yang Tuhan kirimkan untukku. Namun, akhirnya aku harus kembali kehilangan sosok laki-laki yang mampu membuatku tenang. Hatiku sangat sakit melepas kepergiannya, ia adalah malaikat bagiku. Kehadirannya membuat hariku lebih berwarna dan lebih semangat menjalani kenestapaan hidup. Aku sungguh baru menyadari, ia bukan hanya seorang kakak, melainkan lebih dari itu. Usiaku sekarang 17 tahun. Aku mencintai Abang Bona.
***
Tiga bulan setelah Abang Bona pergi, aku mulai berdamai dengan keadaan dan menata kembali hidupku yang sempat kacau. Aku lebih semangat berjualan kue lapis ubi buatan Mamak, kini tidak lagi menghindari sekolahan. Aku sudah bertekad rajin belajar dari buku-buku yang diberi Abang Bona untuk bisa mengikuti program Paket C. Aku juga masih suka mengunjungi pohon besar itu setiap pukul 4 sore untuk belajar atau sekadar mengenang. Terkadang berharap Abang Bona akan datang. Aku tersenyum kecut ketika membayangkan hal itu.
Sebenarnya Mamak tidak suka melihatku berjualan sambil membawa buku, katanya lebih baik aku fokus berjualan karena penjual kue keliling tidak pantas membaca buku tebal. Awalnya aku memang minder, tetapi jika sudah terbiasa aku nyaman saja. Toh, Mamak tidak melarang dan ia tidak pernah bertanya dari mana aku mendapatkan semua buku itu. Suatu malam Mamak masuk ke kamarku dan melihat buku-buku berserakan di atas tempat tidur.
"Kau sedang belajar, Nem? Bagaimana kau mengerti isi buku-buku itu, kau kan tidak sekolah?"
"Nem sedang berusaha mengerti, Mak, makanya Nem belajar. Insya Allah nanti Nem mau ikut Paket C."
"Halaaah .… Kau ada-ada saja, jangan kebanyakan berkhayal. Sudah malam, lebih baik kau tidur. Besok kau harus bangun lebih pagi."
"Iya, Mak."
Aku sudah tidak lagi tersinggung dengan apa pun perkataan Mamak, justru aku semakin semangat untuk memberi pembuktian. Aku selalu ingat kata-kata Abang Bona, "Kamu harus tahu, Nem, saat kita bisa berdamai dengan keadaan, maka kita akan mampu mengikhlaskan segala hal yang menyakitkan."
***
Dua tahun kembali berlalu. Kehidupanku kini terasa lebih baik. Aku sudah tidak berkeliling menjajakan kue lapis ubi, sekarang aku memiliki kios sendiri di tepi jalan raya. Lumayan jauh dari rumah, jadi Mamak jarang ke sini. Naja juga sudah bisa dibawa ke dokter untuk konsultasi setiap sebulan sekali. Semua ini aku peroleh setelah proposal yang kuajukan ke suatu perusahaan swasta lolos didanai. Aku bisa menulis proposal seperti ini karena dulu sering menemani Abang Bona membuatnya, dan sesekali ia mengajariku. Ditambah buku-buku yang ditinggalkannya, terselip hardfile proposal miliknya. Kemudian, aku mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Saat aku membaca pamflet terkait pengajuan dana usaha delapan belas bulan lalu, aku berinisiatif untuk ikut mendaftar. Maka berhari-hari sepulang berjualan, aku menghabiskan sisa siang di warnet. Alhamdulillah … kini aku bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa kekurangan, bahkan sebagian bisa ditabung. Aku juga telah lulus dari program Paket C.
Semenjak Abang Bona pergi, aku suka menuliskan keseharianku di buku harian. Menuliskan segala hal yang kurasa di bangku ini, di bawah pohon besar.
Dear Abang Bona…
Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik di mana pun berada. Sekarang Nem tidak mengayuh sepeda ontel lagi, berkeliling ke banyak tempat untuk menjajakan kue lapis ubi. Nem sudah memiliki kios sendiri dan penghasilannya lebih banyak. Kondisi Naja lebih baik karena setiap sebulan sekali ia rutin berkonsultasi dengan dokter. Mamak juga tidak suka marah lagi. Nem telah lulus Paket C, dan berencana melanjutkan kuliah di kampus Abang dulu. Semua ini karena Tuhan dan kebaikan Abang Bona padaku. Terima kasih. Abang tahu, aku masih suka mendatangi bangku di bawah pohon besar setiap pukul 4 sore seperti rutinitas kita dulu. Aku juga masih menyimpan kado berpita merah yang belum sempat kuberikan saat hari wisuda Abang, sekaligus hari terakhir pertemuan kita. Nem rindu Abang Bona. Nem masih setia menunggu, berharap Abang akan kembali membawa balasan cinta untukku.
– TAMAT –
Pemalang, 28-29 Juli 2020
Tentang Penulis
Dwi Endah Ni'matul Amalia, perempuan yang lahir dan tinggal di Pemalang. Dalam dunia kepenulisan ia tergolong masih pemula. Awalnya, gadis pecinta angka ini tertarik dengan puisi. Namun, kali ini ia sedang belajar menulis cerpen.
Instagram: @endahamalia224
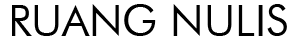


Post a Comment