(Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita
musyrik hingga mereka ber iman (masuk Islam). Sesungguhnya wanita budak yang
mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun ia menarik hatimu…” (QS: al-Baqarah:221).
Burung prenjak mendekor langit, lewat bersuit-suit, pulang ke
sarang. Rumpun ilalang ranggas meliuk-liuk dibelai angin. Seperti senja-senja
jingga sebelumnya, cinta ditaburkan dari langit. Pun aku, menjemput cinta yang
ditaburkan dari langit di wajah seorang pemuda sederhana, yang belakangan ini
bayangnya tak mau pergi dari kepala. Dia memboncengku naik sepeda ke bendungan
di ujung kampung Bani. Tentunya setelah mendapat makian dari Baba-ku karena
melarikan anak gadisnya sejam demi menyaksikan cinta yang ditaburkan dari
langit dalam senja yang megah.
“Berandal! Haiya, beraninya ko rang larikan anak orang! Len On!!!
Kembali kau, Fang Len On!”
Hanya sejam. Untuk sebuah cinta yang hinggap dengan sederhana, yang
tak banyak meminta, dan tak banyak kata untuk membuktikannya. Kami harus pulang
ketika gelap mulai merayap menelan semburat jingga sang senja. Said harus tiba
sebelum adzan maghrib menggema, karena dia-lah muadzinnya masjid kampung kami.
Sering aku tercenung dalam menyimak adzan. Terdengar sangat indah dan
menggetarkan, meskipun aku tak tahu apa yang dilantunkan.
Senja demi senja berganti ratusan kali. Dan senja kali ini, 23
Oktober 1996, Said memboncengku naik sepeda ke padang ilalang. Aku terpaku di
hadapannya, gelisah menunggu kata-kata keluar dari lisannya. Gerimis pun
berubah menjadi hujan yang deras. Kami membiarkan tubuh kami basah dan
kedinginan.
“A Len, seperti yang telah kuutarakan pada Ayahku, bahwa aku ingin
menikahimu. Ayahku yang seorang muslim taat tak mengizinkanku untuk itu. dan
kutahu Baba Liong yang seorang Konghucu taat takkan membiarkan anak gadisnya
dinikahi oleh pemuda yang bersebrangan dengan kepercayaannya…” dia terhenti.
Betapa terkejutnya aku mendengar kata yang tumpah ruah itu. aku
luruh dari berdiriku, mulai terisak dan menggigil. Tak kusangka bahwa di senja
yang bersahaja ini, dia menampar hatiku. Padahal, kami berjanji akan menikah
tahun ini, apapun yang terjadi. Aku dihinggapi kegamangan luar biasa. Luruh
dari tempatku, aku terisak, tak ingin aku terpisahkan dari Said. Aku meremas
ilalang-ilalang tajam, tersayat dan berdarah-darah. Perih, tapi hatiku lebih
perih.
Meski kami miskin, kumal dan buruk, kelurga kecil kami tak pernah
surut akan senyuman. Ya, keluarga. Akhirnya kami menikah meskipun Baba, sejak
keputusan untuk menikah dengan Said kutetapkan, tak mau lagi melihatku
menginjak halaman rumahnya. Baba begitu murka denganku.
“Kau ingin apa saja, sampai mana pun kuturuti meskipun kita ni
miskin. Kau ingin tetap jadi Konghucu atau berubah jadi Kristian, atau Hindu
Budha segala, tak masalah bagiku! Tapi jika kau berani menikah dengan muslim
atau menjadi muslim, lebih baik kau pergi dari rumah ini! Dan aku bukan Baba-mu
lagi!” murka Baba.
“Jika kau berani menampakkan diri halaman rumahku, akan kupotong
lehermu! Awas kau!” teriaknya, mengakhiri murkanya padaku. Baba, Chen dan Chung
Fa, kedua adikku, mengusirku. Ancamannya tak main-main. Maka, dengan kecewa dan
air mata yang menganak sungai, aku cepat-cepat meninggalkan rumah itu, sebelum
leherku benar-benar dipotongnya.
Aku dan Said melarikan diri jauh dari kampung demi memperjuangkan
seekor makhluk yang disebut cinta. Namun, meski sekarang kami jauh dari hidup
berkecukupan, hatiku tenang bersamanya. Aku bukanlah Kristian, apa lagi
penganut Hindu atau Budha. Bukan lagi penganut agama Konghucu karena tidak pula
datang ke Klenteng untuk beribadah, bahkan tidak pula mengikuti suami menjadi
muslimah. Hatiku kosong tanpa Tuhan.
Said masih setia menjadi Said yang dulu, taat dan patuh pada
Tuhannya. Dia shalat, mengaji dan berpuasa. Tapi tak pernah sekali pun ia
mengajakku mengikutinya. Aku selalu dilanda keharuan tiada tara ketika ia
membaca Al Quran. Dalam setiap lekuk tajwidnya, seakan adalah pekik rindu yang
mendalam untuk Tuhannya. Aku menyimak dari luar kamar bacaan ayat-ayatnya,
meski sama sekali tak kumengerti tetapi ketenangan jiwaku dapat kurasakan.
Jika bulan Ramadhan tiba, aku bangun dini hari, memasak, menyiapkan
makan sahur untuk Said. Meski aku tak puasa, aku ikut makan bersamanya. selama
menjadi istrinya, aku tak lagi makan babi dan anjing. Aku makan seperti yang
orang muslim makan, seperti yang Said makan. Dan siangnya aku tak makan, hingga
Said pulang dari tambang timah, menunggunya berbuka puasa. Malamnya, aku tak
tidur menunggunya pulang shalat tarawih dari masjid.
Konflik hebat dalam hatiku tentang Tuhan terjadi ketika hampir
lunas nyawaku dalam proses melahirkan putra pertamaku, Furqan. 9 September
1998, aku mengalami kontraksi hebat. Aku tak lagi punya daya, seakan sejuta
luka tertampung di ‘sana’. Said berusaha menenangkanku yang menjerit-jerit seperti
kurban disembelih. Mulutnya berkomat-kamit melafazkan doa-doa yang tak
kumengerti. Dalam nafas satu-satu, aku merasa membutuhkan suatu kuasa yang amat
besar, yang mampu menolongku dan memudahkan kelahiran putraku. Sekarang aku
sangat membutuhkan Tuhan untuk menyelamatkan anak beranak ini. Tapi Tuhan siapa
yang harus kusebut dalam rintihanku?
Wajah Bidan setengah baya itu mulai panik dan pucat karena begitu
lamanya aku teraniaya tanpa titik terang. Ia sudah berbuat apa saja semampunya.
Sementara itu, Said masih di sampingku, menggenggam tangaku erat seakan tak
ingin kehilanganku. Ia masih bekomat-kamit dalam doa. Dalam doanya kudengar
lamat-lamat berulang kali menyebut Allah. Seperti talah menemukan jawaban dari
pertanyaan, setelah itu, hanya kata “Allah” yang keluar dari mulutku.
“Allah… Allah… Allah,” ucapku. Berharap Allah, Tuhannya Said sudi
menolong aku dan putraku.
Mendadak wajah Said yang cemas berubah menjadi bahagia, senyum
terulas di bibirnya. Dan sesuatu yang tak dapat kujelaskan dalam logika, membuatku
punya daya kembali demi menghadirkan putra sulungku ke dunia. Setiap kumemekik
menyebut Allah, seakan aku menjadi lebih kuat dari sebelumnya.
Kejadian itu membuatku percaya bahwa Tuhan itu ada. Pun membuatku
senantiasa berdoa dalam hati kepada Tuhan yang disebut Allah itu selalu
menolongku, memberiku, dan mengasihiku. Meski begitu, aku belum muslimah.
Begitupun Said, meski ia tahu aku telah percaya pada Allah, ia belum mau
mengenalkanku pada-Nya.
Furqan Sidiq Habibullah, tumbuh menjadi bocah lima tahun yang
tampan dan cedas. Furqan tumbuh menjadi muslim. Tiap ba’da maghrib, Ayahnya
mengajarinya mengaji. Di bawah sinar lampu minyak yang temaram, mereka berdua
seakan dipeluk dalam cinta Tuhan. Makin terharunya aku ketika anak semuda itu
sudah dapat mengaji, dan seperti Ayahnya, setiap lekuk tajwidnya mengadukan
rindu tiada tara seorang hamba kepada Tuhannya.
Pada waktu masuk shalat, Said meminta izin dari mandor tambang
timah untuk pulang sekadar mengajak Furqan shalat di masjid. Biasanya, ba’da
Ashar, Ayahnya mengantarkannya mengaji ke Taikong Habib di masjid raya kampung.
Dan aku yang akan menjemputnya pulang. Menunggunya di halaman masjid, sampai ia
selesai mengaji. Aku memboncengnya dalam kursi rotan di atas boncengan sepeda.
Telapak kakinya kubalut dengan sapu tangan agar tak masuk ke jari-jari ban. Di
jalan tidak jarang ia membacakan surah yang sedang dihafalnya. Saat ia
melantunkan ayat suci, aku diam menyimak. Tapi tak jarang, ia menanyakan
pertanyaan polos yang menampar hatiku.
“Apakah Ibu bisa mengaji? Sebaik apakah Ibu mengaji? Berapa surah
Al Quran yang telah Ibu hapal? Mengapa aku tak pernah melihat Ibu shalat dan
mengaji? Bu, mengapa Ibu tak berjilbab seperti Ibu-ibu yang lain?” itu sebagian
dari celoteh pertanyaannya.
Aku tak pernah menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Anak
sekecil itu, takkan paham bila kuberi pengertian bahwa aku tak bisa membaca
huruf hijaiyah, tak mengerti apa itu mengaji, dan ia takkan mengerti bahwa
Ibunya bukanlah seorang muslim seperti dirinya.
Sebelum Maghrib, biasanya Said sudah pulang dari tambang. Tapi
senja kali ini berbeda, entah apa sebab musababnya hingga adzan Maghrib Said
tak kunjung pulang. Furqan gelisah dan mulai menangis karena Ayahnya belum
pulang untuk pergi ke masjid bersamanya.
“Ibu, di mana Ayah? Mengapa lama sekali Ayah pulang? Aku akan
terlambat shalat Maghrib, Bu!” tangisnya pecah. Aku pun ikut cemas karena Said
selalu pulang tepat waktu. Aku berusaha menenangkan Furqan, tapi tak berhasil.
Yang diinginkannya adalah Ayahnya yang selalu mengajaknya ke masjid.
“Sudahlah, Nak. Jangan menangis. Ayah memang tak bisa mengantarmu
ke masjid sekarang, biar Ibu saja yang mengantarmu. Kau mau, kan?” hiburku,
mengusap air matanya yang berburai-burai di pipi kue terigunya. Perlahan
isakannya reda. Ia minta ditemani berwudhu. Lalu, aku menuntun tangan kecilnya
berjalan ke masjid yang jaraknya tak lebih dari 200 meter.
Aku mengantarnya hingga depan pintu. Furqan mencium tanganku dengan
takzim, lalu masuk. Wajahnya sudah cerah seperti sediakala. Aku menunggunya di
teras masjid, sambil mendengarkan imam mengimami jamaah shalat Maghrib. Aku
termenung untuk beberapa lama. Ada seorang perempuan yang hadir terlambat,
berlari-lari ke masjid. Melihatku, ia berhenti di pintu,
“Nya, tidak shalat?” tanyanya heran. Aku menggeleng.
Aku ingin masuk. Aku ingin mengenakan mukena. Aku ingin shalat
bersama mereka. Aku ingin mengaji. Tapi apakah ‘pemilik’nya mengizinkan manusia
kotor berlumuran dosa memasuki rumah-Nya? Bukankah aku serupa anjing yang
najis?
Pukul 7.45, Furqan telah rapi dengan baju koko merah favoritnya,
yang kubelikan di Tanjong, lebaran lalu. Hari ini adalah hari yang istimewa
untuk Furqanku. Ada acara kelulusan dan perpisahan di TK-nya. Dan Furqan
terpilih tampil membaca hafalan Al Quran. Berseri-seri wajahnya demi menghadapi
hari manis ini. Said mengelap sepeda tua, harta satu-satunya keluarga kami,
memeriksa rem, rantai, dinamo dan kliningannya agar sempurna dipacu ke Jabung-7
kilometer dari kampung kami-juga demi acara putera kami. Pakaian yang
dipakainya pun adalah pakaian terbaiknya. Kemeja bergaris-garis hitam dan
sedikit warna merah, yang juga dibeli pada lebaran tahun lalu.
Aku menjalin rambut menjadi satu kemudian diikat di ujungnya. Dan
dipadu dress hijau bermotif bunga merah yang warnanya sudah luntur. Aku
bergegas karena tak ingin terlambat. Namun ketika Furqan melihatku, ia seperti
melihat domba makan tanaman peliharaannya, tidak suka, marah dan jengkel.
“Mengapa Ibu berpakaian seperti itu?” tanyanya dengan nada kesal.
Aku diam saja, sambil menunduk memakaikan sepatu ke kakinya.
“Ibu! Semua ibu-ibu yang datang akan memakai jilbab, hanya Ibu saja
yang tidak. Kalau Ibu tidak memakai jilbab pergi ke sekolahku, aku takkan pergi
hari ini!” ujarnya, mengancam.Aku tak acuh, menuntunnya keluar rumah untuk
segera berangkat. Said menghampiri kami yang sedang bersitegang.
“Jangan macam-macam, Furqan. Kita sudah terlambat” bentakku. Dia
malah menangis dan meronta dari pegangan tanganku. Furqan mengamuk. Said
menggendong Furqan yang terus meronta-ronta.
“Tenanglah, Nak. Ibumu berjanji besok akan memakai jilbab. Sudah,
sudah jangan menangis. Kita berangkat sekarang, Nak. Kita akan terlambat.
Bukankah kau akan mengaji?” hibur Said.
“Aku akan sangat malu jika Ibu datang ke sekolahku tak berjilbab.
Semua ibu guru dan ibu teman-temanku tentu berjilbab, Yah. Aku inginnya
sekarang… sekarang,” rengeknya. Aku habis kesabaran. Ingin kuberkata padanya
bahwa aku bukan muslim, jadi tak perlu berjilbab, seandainya ia mengerti.
“Ibu tak punya jilbab, Nak…,” ucapku, memberinya pengertian. Dia
buang muka.
“Alas meja kan ada!” jawabnya ketus.
Aku menatap Said, ia mengisyaratkan agar aku cepat. Segera kuturuti
kemauan Furqan, berlari masuk ke dalam rumah. Alas meja ruang tamu kuambil. Aku
berganti baju panjang dan berdiri di depan cermin berusaha memakai alas meja
sebagai jilbab yang menutupi kepalaku. Aku berlari keluar menuju mereka. Said
membantuku memasang jilbab. Dilipat dan dipaskannya ke wajahku, lalu
disimpulnya. Clear!
Furqan berhenti menangis ketika melihatku memakai jilbab.
Sejujurnya aku sangat malu berada di khalayak mengenakan alas meja di kepalaku.
Said tersenyum-senyum melihat wajahku memerah malu. Rasanya aku ingin pulang
saja.
Namun, ketika Furqan tampil di atas panggung membacakan hafalan
surah. Dan belakangan, kutahu yang dibacakannya adalah surah Al-Insyirah dan
Al-Kafirun, lengkap ayat dan tejemahnya. Mataku berkaca-kaca menyaksikan
puteraku tampil di khalayak sebagai muslim, sementara Ibunya masih kafir. Said
menggenggam tanganku erat. Kutahu ia sangat bangga pada Furqan. Anak yang telah
ditancapkan keimanan dalam dadanya, agar besar nanti tak tersesat sepertiku,
yang gamang akan keagamaan. Sungguh, kalimat terakhir surah Al-Kafirun menukik
dari lisannya dan menghujam tepat di jiwaku.
“Bagimu agamamu dan bagiku agamaku” (Terjemah QS. Al-Kafirun 109:6)
Sesungguhnya, perkara ini haruslah dipisahkan. Tak bisa
kucampuradukkan ajaran Islam dan ajaran Konghucu dalam kepalaku, apalagi dalam
rumah tanggaku. Karena meskipun aku percaya Tuhan yang mereka sebut Allah itu
ada, aku tidak menyembah apa yang mereka sembah. Mereka pun tak pernah
menyembah apa yang aku sembah. Berkas-berkas cahaya hidayah menesulupi
kekosongan jiwaku. Aku tersedun sedan menyimak bacaan puteraku, sama seperti
saat aku menyimak bacaan ayat yang dilantunkan suamiku.
Dua hari setelah itu, aku mengucapkan dua kalimah syahadat di
masjid raya kampung, ba’da Ashar. Taikong Habib, Said dan Furqan sebagai saksi
hidup bahwa mulai hari itu aku resmi seorang muslimah dan namaku diganti
menjadi Aisya Zukhrufurrahmi. Seketika itu aku bersujud, berterima kasih kepada
Allah atas hidayah yang dilekatkan ke jiwaku. Aku berterimakasih atas
kesempatan menjalani sisa usiaku sebagai muslimah. Dan aku memohon maaf
kepada-Nya atas segala dosa yang kuperbuat di masa lalu. Ya Allah, aku telah
menemukan-Mu.
Hari-hari berlalu dengan indah dan semakin indah. Aku bahagia
karena aku dapat beribadah dengan mereka. Said dengan sabar mengenalkanku
tentang Islam dari awal, seperti yang kuharapkan bertahun-tahun lalu. Dan lihatlah
kini, inilah madunya. Ia mengajariku tata cara shalat. Shalat pertamaku adalah
shalat Maghrib di masjid, berangkat bersama suami dan puteraku, seperti yang
telah lama kuinginkan. Tetangga tentu heran melihat perubahanku yang kini telah
menjadi muslimah, apalagi kini aku berhijab. Ada saja yang mencemooh
perubahanku. Dengan bisik-bisik, dengan halus dan ada pula yang
terang-terangan.
“Nya Len, sejak kapan orang Ho Pho di pulau ini berpakaian macam
ustazah?! Bagus Nya Len ini membakar dupa di klenteng!” ujar tetangga dengan
ketus. Lihatlah, padahal dia muslim juga yang sepatutnya mendukungku, bukan
menganggap hijrahku ini salah. Aku ini mualaf, keimananku masih sangat rapuh.
Hatiku memang hancur, tapi kumenguat-nguatkan hati bahwa ini semua
adalah bagian dari cobaan, meskipun cobaan itu menyakitkan. Kuingat janji-Nya,
bahwa di balik kesusahan pasti ada kemudahan.
“…karena
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah
kesulitan ada kemudahan..” (Terjemah QS. Al-Insyirah 94:5-6)
Hujan deras sejak pagi hingga ba’da Ashar. Setelah itu rinai-rinai
di senja pucat, bak tirai air tipis berlapis-lapis. Setelah aku menjemput
Furqan dari masjid raya, aku menjerang air di tungku, agar bila Said pulang
nanti ia bisa mandi air hangat. Furqan di ruang tamu bermain mobil-mobilan kayu
sendirian, menunggu Ayahnya pulang dari tambang. Suara sepeda masuk ke
pekarangan. Furqan menghambur dengan riang, keluar demi menyongsong Ayah yang
ditunggunya sejak tadi. Ia tertegun ketika orang yang datang itu bukanlah
lelaki yang ditunggunya.
“Tolong panggilkan Ibumu, Nak,” pinta lelaki tua itu.
Furqan menggangguk dan berlari ke dalam rumah memanggilku yang
berada di depan tungku. Aku menemui lelaki tua tersebut yang kemudian kutahu ia
adalah Wak Kasim. Dengan wajah pias dan bicaranya pun gemetaran, ia mengatakan
padaku bahwa tambang longsor dan Said tertimbun di sana. Aku terperanjat bukan
kepalang. Akalku ditempeleng, aku tak dapat percaya dengan pernyataan Wak
Kasim. Furqan kunaikkan ke boncengan dan kukayuh sepeda ke tambang secepat
buaya muara mengejar mangsa. Aku menerabas tirai-tirai hujan berlapis, air
mataku menetes dan diterbangkan angin. Jilbabku berkibaran. Hatiku memanjatkan
doa-doa kepada Allah, semoga suamiku masih dapat diselamatkan. Aku sangat takut
Said meninggalkanku di saat diriku masih rapuh sebagai muslimah.
Di sana warga berkerumun mencoba menyelamatkan Said dengan
menggali-gali longsoran. Aku menerabas kerumunan dengan kalut, panik dan segala
pikiran bercampur dalam kepalaku. Dengan tanganku kugali tanah longsoran yang
menimpa Said seperti oarang kesurupan. Aku pun tak ingat Furqan kutinggalkan di
mana saat itu karena teramat paniknya. Akhirnya, setelah lama menggali dengan
para warga, aku menemukan tangannya. Tangannya tertengadah. Dadaku sesak
mengetahui itu. Jika tertimbun dalam keadaan terlentang, biasanya kuli tambang
tak selamat. Seperti yang alami Said, ia sudah tak bernyawa. Aku tersedu sedan
memeluk jasad yang diam, dingin, dan pucat.
Jenazah Said dimandikan dan dikafankan oleh keluarganya dan aku
membantu semampuku. Jujur aku belum belajar sampai sana. Hatiku perih sekali
memandangnya terbujur kaku dibalut kafan. Tapi apa boleh buat, ajal sudah
menjadi ketetapan-Nya, tak bisa dimajukan atau dimundurkan waktunya barang
sedetikpun. Setelah dikafankan, Taikong Habib dan warga yang datang ke rumah
duka men-shalat-kan almarhum. Aku ingin ikut shalat jenazah bersama mereka,
tapi aku tak tahu bagaimana caranya.
Aku malu, dan menyingkir ke dapur. Di sana aku makin tersedu-sedu,
aku mohon maaf pada Said karena aku tak bisa shalat jenazah. Aku merasa sangat
bersalah. Dalam hatiku berkata seandainya aku dilahirkan ke dunia ini sebagai
muslimah. Mertuaku menemuiku di dapur. Ia memelukku, menasihatiku agar
mengikhlaskan kepulangan Said kehadapan Allah. Ia menyuruhku agar tabah dan
meredakan tangisku. Tapi tangisku malah makin deras.
“Bu, aku ingin menshalati Said. Tapi aku tak tahu caranya…,” kataku
sambil terisak.
Ia memaklumiku karena aku mualaf yang masih sangat minim
pengetahuan ibadah dan lainnya tentang Islam. Baru dua minggu yang lalu aku
mengikrarkan bahwa aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi
Muhammad utusan Allah, tetapi Said, tumpuanku, diambil-Nya. Aku seperti
layang-layang teraju timpang, tak seimbang.
Furqan kehilangan sosok Ayah yang selalu mendampinginya mengaji dan
beribadah. Aku kehilangan cinta pertamaku, yaang membuatku menemukan Tuhanku.
Aku harus bangkit dari kesedihan. Bagaimanapun hidup harus tetap berlanjut,
Furqan membutuhkanku. Aku pun harus belajar tentang Islam, meski tanpa Said,
jamaah masjid kampung setia mengajarku. Kini, akulah yang mengantar Furqan ke
masjid raya untuk mengaji, ba’da Magrib kami belajar mengaji bersama, tak
jarang ia yang mengajarku. Aku tak memohon kehidupan yang mudah, namun kumemohon
ketegaran hati untuk menghadapi segala ujian. Aku yakin, Allah selalu
menolongku di setiap keterbatasanku.
“Said, terima kasih untuk semua cinta yang indah, karena kau telah
mencintaiku dengan sederhana. Dan terima kasih telah membuatku menemukan cinta
Tuhan yang abadi”
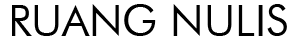


Keren
ReplyDeleteYa Allah aku nangis😭😭😭
ReplyDelete